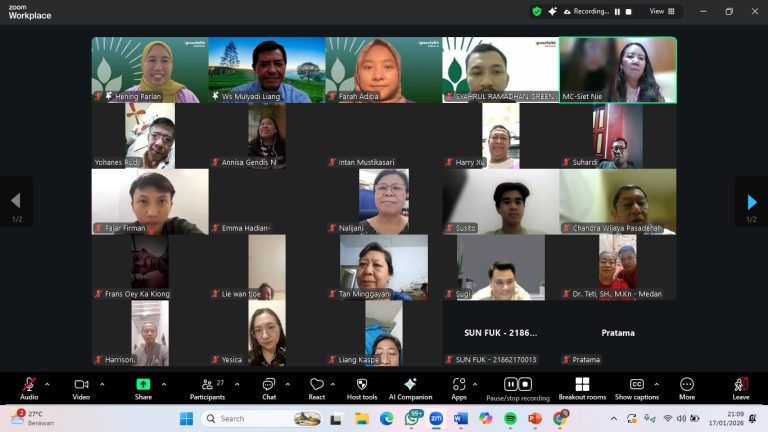Rachel Nindyasari
Refleksi Seorang Gadis dalam Temu Raya Pemuda Sinode GKJ 2025
Lenteraharapan.com – Moga, Rasanya, panas matahari yang menembus sela-sela awan siang itu tidak sepenuhnya menyengat kulit. Padahal, jarum jam telah menunjuk pukul 12.15 WIB. Semilir angin yang menyapu lereng Bukit Gambangan, Kecamatan Moga, Pemalang, menghadirkan kesejukan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Langit tidak benar-benar cerah. Arak-arakan awan putih bergerak perlahan, seolah malu-malu menyibak birunya langit.
Namun justru di situlah letak keindahannya, romantisme alam yang hadir tanpa dibuat-buat, menyatu dengan aura semesta yang menyapa dengan kelembutan.
Dari kejauhan, tampak seorang gadis ayu berkulit kuning langsat berdiri dengan tenang. Namanya terucap pelan namun penuh kesan: Rachel Nindyasari. “Rachel”, dari akar bahasa Ibrani kuno, berarti ewe, artinya seekor domba betina yang lembut, simbol kasih dan kepekaan. Sedangkan “Nindyasari” tak sekadar susunan suku kata, melainkan alunan kidung Jawa yang merapal harapan, nindya berarti utama, luhur dan sari adalah inti, sari kehidupan.
Rachel Nindyasari, dengan demikian, merupakan perwujudan dari kelembutan yang luhur, keindahan yang berakar dalam ketulusan.

Datang sebagai Dirinya Sendiri
Rachel hadir di Temu Raya Pemuda/Remaja (TRP) Sinode GKJ Rayon 1 tahun 2025, bukan sebagai siapa-siapa. Bukan tokoh besar, bukan pula pembicara utama. Ia datang sebagai gadis muda dengan sepasang mata yang menyimpan langit dan senyum yang bisa meredakan hari-hari yang terlihat mendung.
Ia bukan pusat panggung. Namun kehadirannya memantulkan cahaya ke sekelilingnya, seperti bulan yang bersinar bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena setia memantulkan cahaya sang surya.
Sunyi yang Menggugah
Dalam sesi reflektif bertajuk Who Am I, Rachel tenggelam dalam keheningan. Ia duduk diam, menatap lantai, seolah mencari sesuatu yang tercecer, bukan benda, melainkan rasa. Bukan jawaban, tetapi pertanyaan yang tak kunjung selesai.
Ia tak mengucap kata. Tapi suara batinnya menggema dalam ruang sunyi itu, seperti bisikan yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang lembut dan peka.
“Kadang aku merasa berjalan dalam hidup ini seperti mengikuti peta yang bukan aku sendiri yang menggambarnya.” Begitu lirih suara hatinya, nyaris tak terdengar, namun menyentuh siapa saja yang sedang bergumul dengan pertanyaan serupa. Rachel yang lahir di Tangerang, pada tanggal 3 Oktober 2002. Di usianya yang masih muda, ia telah menyelesaikan studi dan kini menjalani kehidupannya sebagai seorang karyawati. Sebuah fase baru yang tak serta merta menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang eksistensinya.
“Aku sering bertanya, siapa aku, sebenarnya? Apakah aku ini sekadar anak dari keluarga yang baik? Atau hanya seseorang yang selalu tersenyum, meski tak selalu tahu kenapa?”
Ia mempertanyakan topeng-topeng yang mungkin dipakainya, dan batas tipis antara menjadi diri sendiri dan memenuhi ekspektasi orang lain.
“Aku mencoba jadi versi terbaik dari diriku, tapi siapa yang menentukan versi terbaik itu? Aku, atau orang lain?” ujarnya dalam hati
Pernyataan itu bukan keluhan, bukan pula keputusasaan. Itu adalah keberanian. Rachel tengah menapaki lorong sunyi pencarian jati diri, wilayah yang tak semua orang berani jamah. Ia tidak datang membawa jawaban, tapi membawa kejujuran. Dan terkadang, kejujuran jauh lebih bernilai daripada kepastian.
Sejenak Menatap Langit
Pukul 12.45 WIB, Minggu, 28 September 2025. Masih di lereng Bukit Gambangan. Rachel berdiri di antara pohon karet, menatap ke arah langit yang biru lembut, terselip di antara ranting dan daun yang bergerak ditiup angin.
“Aku suka warna biru,” ucapnya pelan. “Biru adalah lambang kedamaian.”
Lalu, dengan nada lebih lirih, ia menambahkan:
“Mungkin aku belum tahu siapa aku sepenuhnya. Tapi aku ingin berjalan, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian untuk terus bertanya.”
Doa yang Tak Terucap, Tapi Dirasakan
Rachel adalah jeda yang tenang di tengah riuhnya perjumpaan itu. Ia berjalan pelan di antara waktu dan ruang. Menyapa orang-orang dengan kesederhanaan yang menyentuh. Ada sesuatu dari dirinya yang membuat siapa pun ingin memperlambat langkah, entah karena tutur katanya yang jernih, atau karena sorot matanya yang seolah memahami tanpa perlu banyak bicara.
Bagi Rachel, TRP bukan sekadar agenda tahunan atau kegiatan gereja. Ini adalah altar, tempat ia mempersembahkan waktunya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia percaya bahwa setiap pertemuan adalah dinamika kehidupan, bahwa dalam keramaian, Tuhan menitipkan pesan lewat wajah-wajah yang ditemuinya. Dan ia, dengan rendah hati, mencoba membaca pesan-pesan itu. Seperti hobinya yang suka membaca buku, dalam senyum, dalam pelukan, bahkan dalam diam yang saling memahami, dirinya terus belajar. Membaca kehidupan yang dijalani.
Ia tak banyak bicara, tapi setiap ucapannya mengendap di hati. Ia tidak mencari sorotan, tapi tak bisa diabaikan. Ia seperti doa yang disisipkan di antara kebisingan zaman, pelan, namun sampai ke langit.
Menjelang senja, Rachel tersenyum kecil dan berkata:
“TRP tahun ini sangat mengesankan. Senang sekali bisa mendapatkan keluarga baru dan pengalaman baru. Semoga kita semua sehat dan bisa bertemu kembali di TRP tahun selanjutnya.” pungkasnya (sugeng ph/Red)